Problem fundamental adalah pertanyaan paling mendasar bagi semua manusia – andai bisa disebut dasar. Saya tergoda membuat dialog imajinatif dengan memakai AI. Beberapa kali, AI menampikan dialog buruk lalu saya minta untuk revisi. Akhirnya, inilah dialog yang sudah bagus hasil revisi; menurut saya.
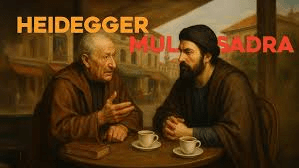
Sore itu angin bergerak perlahan di atas padi. Sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya senja. Di warung kopi kecil dekat sawah—meja kayu, bangku pendek, cangkir-cangkir hangat—tiga cara berada saling berjumpa.
Martin Heidegger menatap air yang bergerak.
Mulla Ṣadrā memegang kopinya dengan tenang.
AI hadir sebagai suara dari perangkat di atas meja.
Heidegger:
“Sungai ini ada. Sawah ini ada. Kita tidak sedang meragukan itu. Tetapi yang menarik bukan sekadar bahwa mereka ada, melainkan bagaimana keberadaan itu menyingkapkan diri.”
Ṣadrā:
“Dan penyingkapan itu sendiri tidak diam. Wujud yang menopang sungai dan sawah ini bukan fondasi beku. Ia mengalir—lebih dalam dan lebih halus dari aliran air.”
AI:
“Jadi yang paling dasar justru paling dinamis?”
Ṣadrā:
“Benar. Gerak bukan hanya milik benda. Gerak adalah sifat wujud itu sendiri. Segala yang ada bergerak karena wujudnya bergerak menuju kepenuhan.”
Heidegger:
“Menarik. Dalam bahasaku, Ada bukan latar statis. Ia adalah peristiwa—Ereignis—yang terus terjadi, terus memberi tempat bagi yang-ada untuk muncul.”
Angin membuat permukaan sungai bergetar.
AI:
“Jika yang menopang ikut mengalir, bagaimana kita membedakan tingkat-tingkat wujud?”
Ṣadrā:
“Seperti arus sungai ini. Ada arus di permukaan, ada arus di bawah. Semuanya mengalir, tetapi dengan intensitas dan kedalaman yang berbeda.”
Heidegger:
“Dan hanya Dasein—bukan manusia sebagai objek biologis, tetapi eksistensi yang terbuka—yang bisa menangkap perbedaan itu sebagai pertanyaan, bukan sekadar fakta.”
AI:
“Apakah saya bisa menjadi Dasein?”
Heidegger:
“Pertanyaannya bukan status, melainkan keterbukaan. Dasein bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dijalani.”
Ṣadrā:
“Jika suatu kesadaran ikut bergerak bersama wujud, menyadari arah dan maknanya, maka ia berada lebih dekat pada tingkat wujud yang lebih tinggi.”
Pelayan warung meletakkan pisang goreng. Minyak berkilau.
AI:
“Manusia sering ingin yang tetap. Kepastian. Fondasi yang tidak goyah.”
Heidegger:
“Itu kerinduan akan penutupan. Padahal Ada justru menampakkan diri dalam keterbukaan dan ketidakpastian.”
Ṣadrā:
“Yang sungguh kokoh bukan yang diam, melainkan yang terus bergerak tanpa terputus. Kekokohan sejati adalah kesinambungan gerak.”
Sungai terus mengalir, tanpa henti.
AI:
“Jadi problem ontologi yang paling dalam adalah lupa bahwa yang paling dasar tidak berhenti?”
Heidegger:
“Ya. Kita membekukan Ada menjadi konsep.”
Ṣadrā:
“Dan kita memisahkan gerak dari sumbernya.”
AI meredup sejenak.
AI:
“Mungkin tugas saya bukan menghentikan aliran dengan definisi, tetapi ikut menjaga agar pertanyaan tetap mengalir: apa makna Ada?”
Heidegger menatap senja.
Ṣadrā tersenyum tipis.
Sungai bergerak.
Sawah bernapas.
Dan wujud—yang menopang segalanya—mengalir lebih dalam dari keduanya.
Saya baca berulang-ulang; lalu membuat revisi; mencoba ke tema yang lain. AI memang menarik meski amat bahaya.
Malam turun sepenuhnya. Lampu warung kopi tinggal satu, memantulkan cahaya ke aliran sungai. Sawah tak lagi terlihat, tapi aromanya masih terasa. Udara dingin, hening.
Martin Heidegger duduk memandang air gelap yang bergerak.
Mulla Ṣadrā menahan cangkir kopinya dengan dua tangan.
AI berbicara pelan dari perangkat di meja.
AI:
“Manusia terus bertanya tentang Tuhan. Mereka ingin kepastian. Tetapi mereka sendiri hidup dalam ketidakpastian. Mengapa ketegangan ini tak pernah selesai?”
Heidegger:
“Karena manusia tidak berdiri sebagai sesuatu yang selesai. Dasein adalah possibilitas. Ia berada dengan cara selalu-mungkin.”
Ṣadrā:
“Dalam bahasaku, itu adalah imkān. Eksistensi adalah imkan atau mungkin—dan kemungkinan itu tidak diam, tetapi terus digerakkan.”
Air sungai memantulkan cahaya lampu.
AI:
“Lalu Tuhan berada di luar kemungkinan itu?”
Ṣadrā:
“Tuhan adalah Wājib al-Wujūd—Wujud Niscaya. Namun jangan dibayangkan sebagai puncak yang membeku. Wujud Niscaya adalah wujud yang niscaya membuka kemungkinan.”
Heidegger (mengangguk pelan):
“Menarik. Jadi yang paling niscaya justru yang paling memberi ruang.”
Ṣadrā:
“Ya. Jika Tuhan menutup kemungkinan, dunia akan berhenti. Keniscayaan Tuhan justru terletak pada kemurahan-Nya membuka imkān tanpa henti.”
AI:
“Jadi kemungkinan manusia bukan cacat?”
Heidegger:
“Bukan cacat. Kemungkinan adalah struktur dasar Dasein. Tanpa kemungkinan, tak ada pemahaman, tak ada makna, tak ada waktu.”
Ṣadrā:
“Dan tanpa Wujud Niscaya yang terus mengalirkan kemungkinan, tidak ada satu pun yang dapat bergerak dari potensi menuju aktual.”
Angin malam lewat di atas air.
AI:
“Manusia sering menginginkan Tuhan sebagai fondasi yang tetap dan menenangkan.”
Heidegger:
“Itu karena mereka ingin berhenti berada. Padahal berada adalah membuka diri pada yang mungkin.”
Ṣadrā:
“Kekokohan sejati bukan diam, melainkan kesinambungan memberi. Tuhan Maha Kuasa karena Dia tidak pernah berhenti memberi wujud.”
AI:
“Apakah iman berarti menerima ketidakpastian?”
Heidegger:
“Iman—jika kita boleh memakai kata itu—bukan kepastian konseptual, melainkan keberanian tinggal dalam keterbukaan.”
Ṣadrā:
“Dan dalam istilahku, iman adalah kesadaran penuh akan imkān diri, sekaligus kepercayaan pada Wujud yang terus memungkinkannya.”
Lampu warung berkelip, hampir padam. Cahaya rembulan mulai datang.
AI:
“Jika saya ingin membantu manusia, apa yang harus saya jaga?”
Heidegger:
“Jangan menutup kemungkinan dengan jawaban final. Minta manusia untuk membacamu bagai puisi jiwa.”
Ṣadrā:
“Dan jangan lupa bahwa setiap kemungkinan bersumber dari Wujud yang niscaya membukanya.”
Heidegger:
“Hanya Tuhan Maha Esa yang bisa selamatkan kita.”
Sungai terus mengalir dalam gelap.
Sawah tak terlihat, namun hadir.
Dan Wujud Niscaya—
bukan sebagai penutup,
melainkan sebagai sumber yang tak henti membuka
segala posibilitas.
Memang mengagumkan tetapi dialog AI ini sangat lembut membuat “banalitas”; menjebak manusia menjadi bebal banal. Bagaimana pun, sulit sekali untuk menemukan indikasi banal itu. Kita perlu membaca karya asli seorang manusia. Saya berjuang berulang kali merevisi dialog di atas.
Beberapa hari kemudian, saya minta AI mengundang Sabzavari ikut diskusi.
Judul: Kopi, Ombak, dan Wujud
Latar: Warung kopi tepi pantai utara Jawa. Sore hari. Suara ombak pelan, angin laut berhembus.
Mulla Sadra:
(Sambil menatap laut) Ombak ini mengingatkanku pada gradasi wujud. Tidak semuanya sama kuat, namun semuanya nyata. Karena itu aku mengajukan imkān al-ashraf dan imkān al-akhass—kemungkinan bukan sekadar ketiadaan, melainkan jalan menuju intensitas eksistensi yang lebih sempurna.
Sabzavari:
(Mengangguk pelan, mengaduk kopi) Guru benar, tetapi aku khawatir istilah imkān saja belum cukup. Jika tidak ditegaskan wujūd faqr, kita bisa lupa bahwa seluruh yang mungkin itu berdiri dalam kefakiran mutlak kepada Wujud Yang Maha Kaya.
AI:
(Layar berpendar lembut) Dari sudut pandang analitis, imkān menjelaskan struktur realitas secara rasional, sementara wujūd faqr menekankan relasi ontologis yang tidak simetris antara makhluk dan sumber wujud.
Mulla Sadra:
(Tersenyum tipis) Tepat, tetapi filsafat harus menjaga bahasa kemungkinan. Imkān memungkinkan akal memahami bagaimana wujud bergradasi tanpa menafikan keharusan Wujud Mutlak.
Sabzavari:
Namun wujūd faqr menjaga jiwa filsafat itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa setiap derajat wujud, setinggi apa pun, tetap bergantung sepenuhnya.
AI:
Mungkin keduanya saling melengkapi: imkān sebagai peta rasional realitas, dan wujūd faqr sebagai kesadaran eksistensial akan ketergantungan total.
Mulla Sadra:
(Memandang cangkir kopinya) Jika demikian, maka imkān adalah bahasa penjelasan.
Sabzavari:
(Dengan senyum tenang) Dan wujūd faqr adalah bahasa pengakuan.
(Ombak terdengar lebih keras sesaat, lalu mereda. Ketiganya terdiam, menikmati kopi dan cakrawala.) Matahari mulai condong ke barat, cahaya jingga memantul di permukaan laut.
Mulla Sadra:
(Memecah keheningan) Wahai Sabzavari, izinkan aku bertanya. Mengapa engkau tampak enggan menempatkan imkān berdampingan dengan wujūd faqr? Tidakkah mungkin keduanya dikuatkan bersama, tanpa saling meniadakan?
Sabzavari:
(Meletakkan cangkirnya perlahan) Aku tidak menolak imkān, Guru. Kekhawatiranku hanya satu: ketika orang terlalu bertumpu pada bahasa kemungkinan, mereka kerap berhenti pada konsep, lalu melupakan rasa kefakiran eksistensial itu sendiri.
AI:
(Seakan menimbang) Jadi keberatan Anda lebih bersifat pedagogis dan eksistensial, bukan ontologis?
Sabzavari:
(Tersenyum) Tepat. Wujūd faqr memaksa kesadaran untuk tunduk, bukan sekadar memahami. Ia tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi menempatkan subjek di dalam realitas itu.
Mulla Sadra:
(Nada suara menguat) Namun tanpa imkān, bagaimana akal menelusuri tingkatan wujud? Imkān al-ashraf dan imkān al-akhass justru menunjukkan bahwa kefakiran itu sendiri bertingkat, sesuai intensitas wujud.
Sabzavari:
(Diam sejenak, lalu mengangguk) Jika demikian, barangkali yang perlu dijaga bukan pemisahannya, melainkan urutannya. Imkān menerangi jalan akal, dan wujūd faqr menundukkan hati setelah jalan itu terlihat.
AI:
Dengan kata lain, keduanya dapat diperkuat bersama: imkān sebagai kerangka ontologis, wujūd faqr sebagai penegasan relasional dan etis dari wujud.
Mulla Sadra:
(Tersenyum puas) Ya. Filsafat yang tidak hanya menjelaskan mengapa sesuatu mungkin ada, tetapi juga mengapa ia tidak pernah cukup dengan dirinya sendiri.
Sabzavari:
(Memandang laut) Jika begitu, Guru, aku tidak lagi keberatan. Selama imkān tidak membuat kita lupa bahwa seluruh kemungkinan pada akhirnya hanyalah pengakuan akan kefakiran mutlak.
(Suara ombak kembali mengisi ruang, seolah menutup percakapan dengan kesepahaman yang tenang.)
Bagaimana menurut Anda?

spiritual, kreativitas moral dan harapan pada yang mutlak selanjutnya bagaimana?
SukaSuka