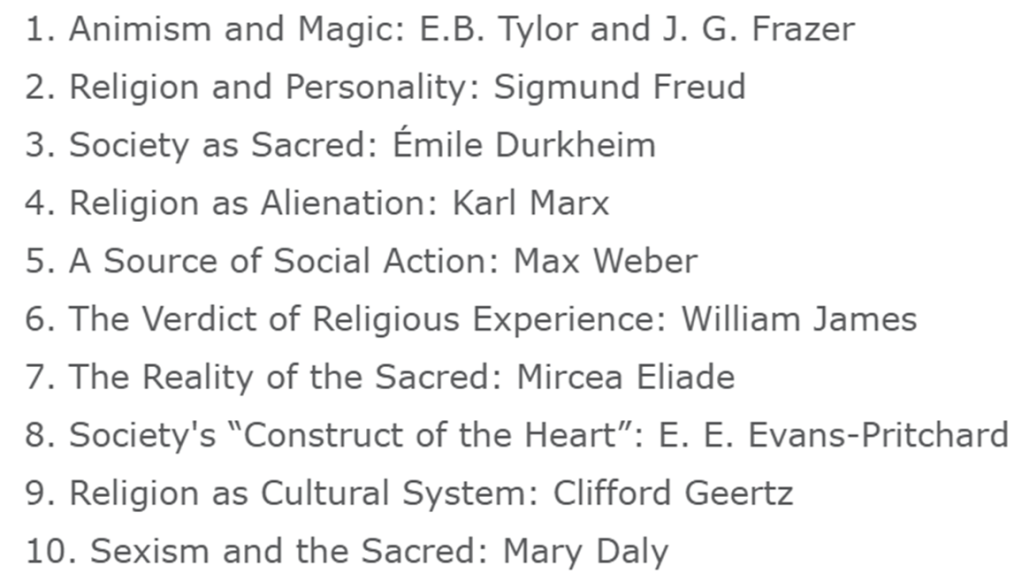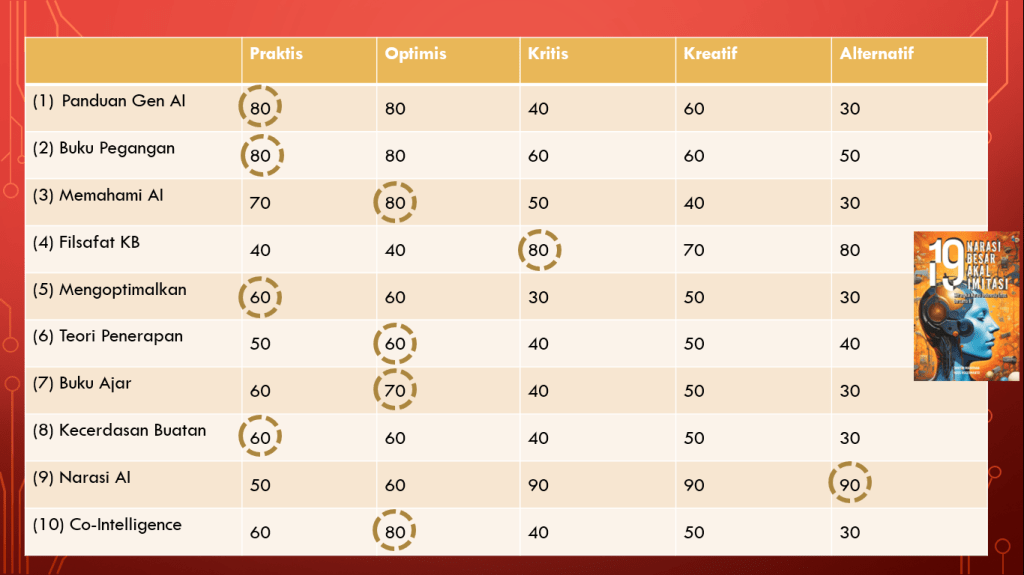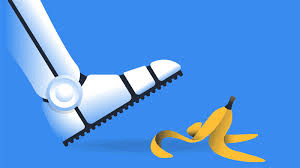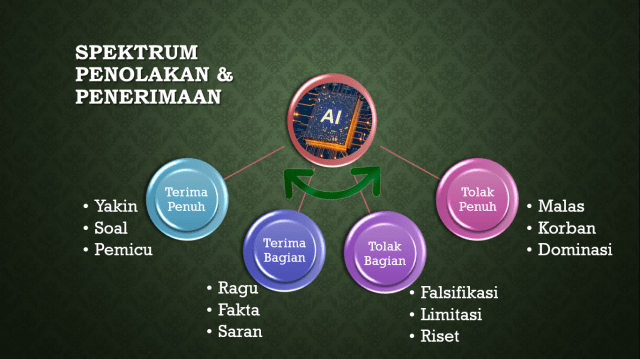Selalu ada buku yang mempesona. Buku baru dari Kohl membahas tema freedom versi Kant dari perspektif yang segar.
Umumnya, manusia sadar bahwa kita bebas memilih. Anda bebas milih berbuat baik atau lainnya. Kohl lebih luas menyatakan, “Kita bebas mikir. Atau, kita bisa berpikir hanya karena kita bebas untuk mikir itu.” Dan terakhir, kita bebas untuk menikmati hidup dan setelah kehidupan kita.
1. Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab Moral
2. Kebebasan Mikir dan Kajian Sains
3. Kebebasan Estetika untuk Cinta
4. Ringkasan
5. Diskusi
Saya menemukan ide sangat penting dari Kohl ada di awal bab X yang merangkum seluruh argumen; kemudian melanjutkan ke bab terakhir yaitu bab X. Kita akan membahas dengan mengutip ide paling penting itu.
1. Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab Moral
For Kant the belief in free will is the metaphysical belief that we possess a supersensible causal power that is not determined by foreign causes. His transcendental idealism is a necessary but insufficient condition for justifying this belief: by restricting the scope of the deterministic causality of nature to sensible phenomena, Kant’s idealism makes ontological space for the existence of a supersensible free causality without showing that this space is (or really could be) filled. This raises the central question of how Kant seeks to justify the belief in free will.
“Bagi Kant, kepercayaan pada kehendak bebas adalah kepercayaan metafisik bahwa kita memiliki kekuatan kausal supraindrawi yang tidak ditentukan oleh sebab-sebab asing. Idealisme transendentalnya adalah syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk membenarkan kepercayaan ini: dengan membatasi ruang lingkup kausalitas deterministik alam pada fenomena indrawi, idealisme Kant membuat ruang ontologis bagi keberadaan kausalitas bebas supraindrawi tanpa menunjukkan bahwa ruang ini terisi (atau benar-benar dapat terisi). Hal ini menimbulkan pertanyaan utama tentang bagaimana Kant berusaha membenarkan kepercayaan pada kehendak bebas.”
Kehendak bebas (free will) itu valid meski tidak bisa dipahami. Hanya saja kita bisa memahami bahwa free will itu tidak bisa dipahami.
A highly distinctive feature of Kant’s view is that he does not try to construct a metaphysical theory for the metaphysical belief in free will: he does not give a theoretical account of how the causality of freedom operates, how it produces physical effects in the phenomenal world, or why free agents act and cause specific effects at particular places and times. Since the belief in freedom is theoretically incomprehensible to us, it is consigned to the normative standpoint from which we consider how we ought to act. This belief does not figure in the empirical standpoint which is focused on observing, explaining, and predicting the
behavior of phenomenal objects (including ourselves). From the normative practical standpoint, we can form a determinate representation of our supersensible (noumenal) causality because our pure self-consciousness as autonomous moral agents provides a positive and objective, though only practical (thus theoretically fruitless) content or meaning for the idea of an atemporal causality.
“Ciri khas pandangan Kant adalah bahwa ia tidak mencoba membangun teori metafisik untuk kepercayaan metafisik pada kehendak bebas: ia tidak memberikan penjelasan teoretis tentang bagaimana kausalitas kebebasan beroperasi, bagaimana ia menghasilkan efek fisik di dunia fenomenal, atau mengapa agen bebas bertindak dan menyebabkan efek tertentu di tempat dan waktu tertentu. Karena kepercayaan pada kebebasan secara teoritis tidak dapat dipahami oleh kita, maka ia dimasukkan ke dalam sudut pandang normatif yang darinya kita mempertimbangkan bagaimana kita seharusnya bertindak. Kepercayaan ini tidak termasuk dalam sudut pandang empiris yang difokuskan pada pengamatan, penjelasan, dan prediksi perilaku objek fenomenal (termasuk diri kita sendiri). Dari sudut pandang normatif-praktis, kita dapat membentuk representasi pasti dari kausalitas supersensible (noumenal) kita karena kesadaran diri kita yang murni sebagai agen moral yang otonom memberikan konten atau makna yang positif dan objektif, meskipun hanya praktis (dengan demikian secara teoritis tidak membuahkan hasil) untuk gagasan kausalitas atemporal.”
Secara moral, kita sadar bahwa kita tanggung jawab atas pilihan bebas kita. Pencuri dan koruptor wajib masuk penjara. Orang baik maka bahagia hidup dan matinya. Bagaimana pilihan bebas itu bisa terhubung dengan alam yang deterministik? Kant tidak menjelaskan hubungan ini karena memang tidak akan bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Untuk apa membahas sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Agar kita bisa menjelaskan bahwa hubungan tersebut memang tidak bisa dijelaskan. Sains alam akan gagal menjelaskan kehendak bebas.
2. Kebebasan Mikir dan Kajian Sains
Because Kant’s doctrine seeks to vindicate the belief in a theoretically
inscrutable type of causality, it must provide reasons for rejecting naturalistic, compatibilist conceptions of free will which avoid the cost of theoretical incomprehensibility. Kant gives two arguments to support his stance that if (as a naturalistic worldview contends) there were merely the causality of nature this would eliminate the only kind of free will worth having. First, the naturalistic claim that all our acts of practical judgment are empirically conditioned is incompatible with the unconditional objective necessity of our moral judgments.
Second, the naturalistic claim that we are causally necessitated to make a particular choice on any given occasion is incompatible with the presumption that we are governed by rational, categorical moral oughts: a presumption which presupposes both the power to act from duty and the privative option to act contrary to duty.
“Karena doktrin Kant berusaha membenarkan kepercayaan pada jenis kausalitas yang secara teoritis tidak dapat dipahami, doktrin tersebut harus memberikan alasan untuk menolak konsepsi naturalistik; dan (menolak) kompatibilis tentang kehendak bebas yang menghindari biaya ketidakpahaman teoritis. Kant memberikan dua argumen untuk mendukung pendiriannya bahwa jika (seperti yang dikemukakan oleh pandangan dunia naturalistik) hanya ada kausalitas alam, maka ini akan menghilangkan satu-satunya jenis kehendak bebas yang layak dimiliki.
Pertama, klaim naturalistik bahwa semua tindakan penilaian praktis kita dikondisikan secara empiris tidak sesuai dengan keharusan objektif tanpa syarat dari penilaian moral kita.
Kedua, klaim naturalistik bahwa kita secara kausal diharuskan untuk membuat pilihan tertentu pada setiap kesempatan tidak sesuai dengan anggapan bahwa kita diatur oleh keharusan moral yang rasional dan kategoris: anggapan yang mengandaikan baik kekuatan untuk (a) bertindak berdasarkan kewajiban maupun pilihan privatif untuk (b) bertindak bertentangan dengan kewajiban.”
Sains Gagal Menjelaskan Kebebasan
Kant menolak klaim dari sains alam, atau naturalistik. Karena kebebasan tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh sains. Peran sains adalah sekedar membantu untuk menjelaskan bahwa kebebasan tidak bisa dijelaskan oleh sains.
Freedom of will is not the only kind of freedom that plays a central role in Kant’s doctrine. In Kant’s considered view we possess a freedom of thought which yields a distinctive species of transcendental freedom even though it lacks the “true causality” to produce external objects as opposed to mere representations of existent objects. Our theoretical intellect is a source of autonomous cognitive laws and goals whose objective rational necessity is incompatible with the assumption that our theoretical representations are conditioned by foreign (natural or super-natural) causes. We must presuppose the objective rational necessity of our pure theoretical concepts (such as “causality”) and cognitive laws (such as the general causal principle) in our theoretical judgments, especially in judgments that seek to provide objective naturalistic explanations for sensible phenomena. Our empirical judgments about nature result from a sensibly affected but absolutely spontaneous (yet also non-voluntaristic) capacity for autonomous cognitive self-determination. Since our transcendental freedom of thought is a necessary condition for our actual objective cognition and knowledge of nature, we can know that our noumenal selves possess transcendental freedom of thought. This does not show, however, that our noumenal selves also possess the transcendental causality of a free will.
“Kebebasan berkehendak bukanlah satu-satunya jenis kebebasan yang memainkan peran utama dalam doktrin Kant. Dalam pandangan Kant, kita memiliki kebebasan berpikir yang menghasilkan jenis kebebasan transendental yang khas meskipun kebebasan tersebut tidak memiliki “kausalitas sejati” untuk menghasilkan objek eksternal yang bertentangan dengan sekadar representasi objek yang ada.
Intelek teoritis kita adalah sumber hukum dan tujuan kognitif otonom yang kebutuhan rasional objektifnya tidak sesuai dengan asumsi bahwa representasi teoritis kita dikondisikan oleh sebab-sebab asing (alami atau supranatural). Kita harus mengandaikan kebutuhan rasional objektif dari konsep-konsep teoritis murni kita (seperti “kausalitas”) dan hukum-hukum kognitif (seperti prinsip kausal umum) dalam penilaian teoritis kita, terutama dalam penilaian yang berusaha memberikan penjelasan naturalistik objektif untuk fenomena yang masuk akal.
Penilaian empiris kita tentang alam dihasilkan dari kapasitas yang dipengaruhi secara masuk akal, tetapi benar-benar spontan (namun juga non-voluntaristik), untuk penentuan nasib sendiri kognitif yang otonom. Karena kebebasan berpikir transendental kita merupakan syarat mutlak bagi kognisi objektif dan pengetahuan kita tentang alam, kita dapat mengetahui bahwa diri noumenal kita memiliki kebebasan berpikir transendental. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa diri noumenal kita juga memiliki kausalitas transendental dari kehendak bebas.”
Kehendak Bebas Geser ke Mikir Bebas
Kehendak bebas didasarkan oleh kebebasan berpikir. Meski kehendak bebas tampak lebih “nyata” dari mikir bebas; tapi mikir bebas bisa lebih utama. Lagi pula, kita hanya bisa berpikir bila mikir itu bebas. Kebalikannya tidak bisa terjadi; karena bila mekanistik deterministik maka konsekuensinya adalah kita tidak bisa berpikir. Jadi dari berpikir bebas, sebagai dasar, kemudian menuju kehendak bebas.
Kant attempts to legitimize the belief in free will through a complex twopronged approach. In Kant’s view our ordinary (pre-philosophical) moral self-consciousness yields knowledge that we possess freedom of will: common agents possess certain knowledge of their moral duties and they (at least implicitly) recognize that they could not possess such normative-practical knowledge unless they had free will. This account of how our common moral self-consciousness justifies our belief in noumenal free will invites the objection that normative practical premises cannot sufficiently justify a determinate yet theoretically inscrutable metaphysical belief in a supersensible causality that produces sensible effects. This objection is fueled by a naturalistic view which insists that we must subject every item of our conscious awareness, including our representation of the moral law, to the physiological explanations of theoretical reason. Rather than allowing our pure moral self-consciousness to justify our belief in noumenal free will, naturalists seek to debunk the alleged purity and rational necessity of our moral self-awareness by viewing our moral representations as empirically conditioned figments of the brain. Kant defends the integrity of our moral consciousness and thereby the epistemic basis of the belief in free will against this naturalistic challenge by invoking our freedom of thought. Naturalistic cognizers cannot presume that every aspect of our conscious awareness must be explicable via natural causes because the objective validity of their naturalistic explanations requires an empirically unconditioned, hence naturalistically inexplicable theoretical consciousness of a priori necessary cognitive laws. Since naturalistic cognizers must presuppose their freedom of thought, they cannot coherently debunk the belief in free will. This argument does not yield a theoretical proof of free will. Rather, it serves as a defense of the epistemically prior purely moral proof.
“Kant mencoba melegitimasi kepercayaan pada kehendak bebas melalui pendekatan bercabang dua yang kompleks. Dalam pandangan Kant, (a) kesadaran diri moral kita yang biasa (pra-filosofis) menghasilkan pengetahuan bahwa kita memiliki kebebasan berkehendak: pelaku umum memiliki pengetahuan tertentu tentang tugas moral mereka dan mereka (setidaknya secara implisit) mengakui bahwa mereka tidak dapat memiliki pengetahuan normatif-praktis tersebut kecuali mereka memiliki kehendak bebas. Uraian tentang bagaimana kesadaran diri moral kita yang umum membenarkan kepercayaan kita pada kehendak bebas noumenal ini mengundang keberatan bahwa premis normatif-praktis tidak dapat secara memadai membenarkan kepercayaan metafisik yang pasti namun secara teoritis tidak dapat dipahami pada kausalitas supersensible yang menghasilkan efek yang masuk akal. Keberatan ini didorong oleh pandangan naturalistik yang menegaskan bahwa kita harus menundukkan setiap item kesadaran sadar kita, termasuk representasi kita tentang hukum moral, pada penjelasan fisiologis dari alasan teoritis.
Alih-alih membiarkan kesadaran moral murni kita membenarkan kepercayaan kita pada kehendak bebas noumenal, naturalis berusaha untuk menyanggah dugaan kemurnian dan kebutuhan rasional kesadaran moral kita dengan melihat representasi moral kita sebagai rekaan otak yang dikondisikan secara empiris.
Kant membela integritas kesadaran moral kita dan dengan demikian basis epistemik kepercayaan pada kehendak bebas terhadap tantangan naturalistik ini dengan (b) menyerukan kebebasan berpikir kita. Pengenal naturalistik tidak dapat berasumsi bahwa setiap aspek kesadaran kita harus dapat dijelaskan melalui sebab-sebab alami karena validitas objektif dari penjelasan naturalistik mereka memerlukan kesadaran teoretis yang tidak dikondisikan secara empiris, karenanya tidak dapat dijelaskan secara naturalistik dari hukum-hukum kognitif yang diperlukan secara apriori. Karena pengenal naturalistik harus mengandaikan kebebasan berpikir mereka, mereka tidak dapat secara koheren menyanggah kepercayaan pada kehendak bebas. Argumen ini tidak menghasilkan bukti teoritis kehendak bebas. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai pembelaan terhadap bukti moral murni yang secara epistemik lebih dulu.”
Sains alam mengandalkan asumsi ada hukum universal yang tidak empiris; misal kausalitas. Karena kausalitas tidak empiris maka sains tidak bisa menjelaskan, atau membuktikan, kausalitas; justru sains membutuhkan kausalitas. Dan masih banyak teori-teori yang tidak bisa dijelaskan secara empiris; termasuk kehendak bebas tidak bisa dijelaskan oleh sains empiris. Kita membutuhkan rute lain untuk menjelaskan kehendak bebas: apakah akan bisa dijelaskan?
3. Kebebasan Estetika untuk Cinta
This concludes my reconstruction of Kant’s doctrine as an account of our moral freedom of will and our epistemic freedom of thought. There is, however, one further important angle to Kant’s views on freedom that a systematic interpretation cannot ignore. I have focused on the two distinctive species of transcendental freedom which play a central role, respectively, in Kant’s moral philosophy and epistemology. In both cases, the relevant kind of free agency is a form of autonomous self-determination where the subject acts (chooses or thinks) under
self-given rational laws. But Kant also brings up the idea of freedom in his aesthetics: he invokes the freedom of our imagination as enabling both our aesthetic production of beauty (in art) and our aesthetic experience of beauty (in art and nature). Can we fruitfully integrate Kant’s appeal to freedom of imagination with his views on freedom of will and freedom of thought? Or must we regard his appeal to aesthetic freedom of imagination as an aberration from his standard conception of freedom, a result which would disrupt the unity of his doctrine? The latter diagnosis may seem unavoidable in light of Kant’s insistence that freedom of imagination is a lawless freedom, namely, a freedom from the rational laws legislated by our higher intellectual faculties.
“Ini menyimpulkan rekonstruksi saya atas doktrin Kant sebagai penjelasan tentang kebebasan moral kehendak dan kebebasan epistemik berpikir kita. Namun, ada satu sudut pandang penting lebih lanjut tentang pandangan Kant tentang kebebasan yang tidak dapat diabaikan oleh interpretasi sistematis. Saya telah berfokus pada dua spesies kebebasan transendental yang berbeda yang masing-masing memainkan peran sentral dalam filsafat moral dan epistemologi Kant. Dalam kedua kasus tersebut, jenis kebebasan yang relevan adalah bentuk penentuan nasib sendiri yang otonom di mana subjek bertindak (memilih atau berpikir) di bawah hukum rasional yang diberikan sendiri.
Namun, Kant juga mengemukakan gagasan tentang kebebasan dalam estetikanya: ia menyerukan kebebasan imajinasi kita sebagai sesuatu yang memungkinkan produksi estetika keindahan (dalam seni) dan pengalaman estetika keindahan (dalam seni dan alam). Dapatkah kita secara berhasil mengintegrasikan seruan Kant tentang kebebasan imajinasi dengan pandangannya tentang kebebasan kehendak dan kebebasan berpikir? Atau haruskah kita menganggap seruannya terhadap kebebasan estetika imajinasi sebagai penyimpangan dari konsepsi standarnya tentang kebebasan, suatu hasil yang akan mengganggu kesatuan doktrinnya? Diagnosis terakhir mungkin tampak tak terelakkan mengingat desakan Kant bahwa kebebasan imajinasi adalah kebebasan tanpa hukum, yaitu, kebebasan dari hukum-hukum rasional yang ditetapkan oleh kemampuan intelektual kita yang lebih tinggi.”
Kebebasan ketiga adalah kebebasan estetika: kebebasan jatuh cinta; kebebasan menikmati keindahan; kebebasan rindu kepada yang merdu. Kebebasan penilaian estetika yang mengandalkan kebebasan imajinasi ini melampaui aturan rasional. Bisakah disatukan dengan kebebasan rasional?
In the concluding part and chapter of this book, I argue that despite this central difficulty we can find a place for aesthetic freedom of imagination in Kant’s systematic doctrine. If we take a certain (admittedly controversial) approach towards Kant’s aesthetics and if we allow ourselves some leeway in applying Kant’s strict definition of transcendental freedom as autonomy, then we can view freedom of imagination as a further (third) distinctive species of transcendental freedom whose lack of determination by intellectual laws uniquely captures the distinctive character of our aesthetic (as opposed to moral or epistemic) self-activity.
“Pada bagian dan bab penutup buku ini, saya berpendapat bahwa terlepas dari kesulitan utama ini, kita dapat menemukan tempat bagi kebebasan estetika imajinasi dalam doktrin sistematis Kant. Jika kita mengambil (a) pendekatan tertentu (yang diakui kontroversial) terhadap estetika Kant dan jika (b) kita memberi diri kita kelonggaran dalam menerapkan definisi ketat Kant tentang kebebasan transendental sebagai otonomi, maka kita dapat memandang kebebasan imajinasi sebagai spesies kebebasan transendental (ketiga) yang lebih jauh yang khas, (c) yang kurangnya penentuan oleh hukum intelektual secara unik menangkap karakter khas aktivitas diri estetika kita (sebagai lawan dari moral atau epistemik).”
Kita bisa menyimpulkan bahwa kebebasan estetika adalah selaras, dan memperdalam, dengan kebebasan moral dan intelektual. Bebas merasa.
But instead of demoting the powers of imagination as being merely analogous to genuine moral or epistemic freedom, we should rather say that the imagination genuinely exemplifies Kant’s conception of transcendental freedom in a highly distinctive manner that accords with the peculiar character of aesthetic as opposed to moral or epistemic activity. Consider here the merits of my key proposal (call it (P)) that the free imagination is loosely governed by indeterminate rational norms. On the one hand, (P) defuses the worry that the free imagination stands under no rules whatsoever and must thus be viewed as an arbitrary liberty of indifference whose products lack universal-intersubjective validity. This worry is clearly the central motive for Kant’s positive definition of freedom as a rulegoverned power. On the other hand, (P) also prevents an objectivist, rationalistic over-intellectualization of imaginative freedom: it avoids the implausible assimilation of free aesthetic production and experience to other (moral, epistemic) types of free agency which have a squarely cognitivist-intellectual character that requires rigid, determinate governance by objective rational laws. Since (P) accounts for both the universal validity and the irreducible subjectivity of our aesthetic representations, it yields a philosophical analysis of taste which (unlike purely subjectivizing or overly intellectualizing aesthetics) remains true to its authentic character.
“Namun, alih-alih merendahkan daya imajinasi sebagai sesuatu yang sekadar analog dengan kebebasan moral atau epistemik sejati, kita lebih baik mengatakan bahwa imajinasi benar-benar menggambarkan konsepsi Kant tentang kebebasan transendental dengan cara yang sangat khas yang sesuai dengan karakter khusus estetika yang bertentangan dengan aktivitas moral atau epistemik.
Pertimbangkan di sini manfaat dari usulan utama saya (sebut saja (P)) bahwa imajinasi bebas diatur secara longgar oleh norma-norma rasional yang tidak pasti. Di satu sisi, (P) meredakan kekhawatiran bahwa imajinasi bebas tidak berada di bawah aturan apa pun dan dengan demikian harus dipandang sebagai kebebasan sewenang-wenang yang tidak acuh yang produknya tidak memiliki validitas universal-intersubjektif. Kekhawatiran ini jelas merupakan motif utama definisi positif Kant tentang kebebasan sebagai kekuatan yang diatur oleh aturan.
Di sisi lain, (P) juga mencegah intelektualisasi berlebihan yang bersifat objektivis dan rasionalistik terhadap kebebasan imajinatif: ia menghindari asimilasi yang tidak masuk akal dari produksi dan pengalaman estetika bebas dengan jenis-jenis agensi bebas (moral, epistemik) lain yang memiliki karakter intelektual-kognitif yang mengharuskan tata kelola yang kaku dan pasti oleh hukum-hukum rasional yang objektif. Karena (P) memperhitungkan validitas universal dan subjektivitas yang tidak dapat direduksi dari representasi estetika kita, ia menghasilkan analisis filosofis tentang selera yang (tidak seperti estetika yang murni subjektif atau terlalu intelektual) tetap setia pada karakter autentiknya.”
Kebebasan rasa selaras dengan aturan rasional yang longgar dan tidak didominasi oleh aturan apa pun.
Admittedly, there is no way of getting around the fact that the imagination lacks autonomy in the precise sense that goes into Kant’s positive definiens. This is because the free imagination does not give its governing rules to itself but takes them from our higher intellectual faculties. For some, this might be enough to show that we cannot speak of genuine freedom here. However, we might also say that the free imagination has its own peculiar, sui generis form of autonomy, “the autonomy of taste” (KU, 5:282). Imaginative activity (in aesthetic production and experience) can be understood as a special form of autonomy for two reasons.
“Harus diakui, tidak ada cara untuk menghindari fakta bahwa imajinasi
tidak memiliki otonomi dalam pengertian yang tepat yang terkandung dalam definiens positif Kant. Ini karena imajinasi bebas tidak memberikan aturan yang mengaturnya kepada dirinya sendiri tetapi mengambilnya dari kemampuan intelektual kita yang lebih tinggi. Bagi sebagian orang, ini mungkin cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak dapat berbicara tentang kebebasan sejati di sini. Namun, kita juga dapat mengatakan bahwa imajinasi bebas memiliki bentuk otonominya sendiri yang unik dan sui generis, “otonomi rasa” (KU, 5:282). Aktivitas imajinatif (dalam produksi dan pengalaman estetika) dapat dipahami sebagai bentuk otonomi khusus karena dua alasan.”
First, the aesthetic imagination positively relates itself to, i.e., invites guidance and direction from norms of understanding and reason that are autonomous in the strict or primary sense. Although these rules do not arise from the imagination itself, they are still not “foreign” to the imagination since they originate in the free unified human mind (Gemüt) that includes the imagination as an integral part. Against this, one might insist that the rules governing the aesthetic imagination are detached from, hence foreign to, its own mode of operation. This is because, one might hold, the aesthetic value created by free imaginative activity is independent from the rules that direct such activity: the greatest expressions of moral or epistemic value result from our strict conformity to the autonomous laws governing our free will or understanding, whereas original beauty arises only when our free imagination does not fully conform to the rules that govern it.
However, if the imagination creates or appreciates something beautiful, then its activity does comply with the norms governing such creation or appreciation. To be sure, this sense of compliance is not the same as in moral or epistemic cases, but that is just because the corresponding type of rule-governedness is different: if the aesthetic imagination operates successfully, it satisfies the norms which direct it in the one and only, indeterminate sense that loose (as opposed to strict lawlike) norm-governedness requires (or enables). For instance (cf. Section X.3), the imagination successfully complies with reason’s vague directive to obtain a maximum of representational content if it fittingly combines and magnifies given sensible manifolds in a non-mundane, aesthetically pleasing manner. Moreover, the aesthetic value arising from free imaginative activity is essentially tied to the rules that govern such activity: since all beauty involves a “sensualizing of moral ideas” (KU, 5:356), and since (as we saw) moral ideas play a key role in guiding aesthetic creation and appreciation, the moral value contained in these ideas is integrally connected (though not identical) to the aesthetic value of beauty. Hence, the intellectual norms governing the free imagination are not foreign to the distinctive value it seeks to create via its aesthetic mode of operation.
“Pertama, imajinasi estetika berhubungan positif dengan, yaitu, mengundang bimbingan dan arahan dari norma-norma pemahaman dan nalar yang otonom dalam pengertian yang ketat atau utama. Meskipun aturan-aturan ini tidak muncul dari imajinasi itu sendiri, aturan-aturan tersebut tetap tidak “asing” bagi imajinasi karena aturan-aturan tersebut berasal dari pikiran manusia yang bebas dan terpadu (Gemüt) yang mencakup imajinasi sebagai bagian integral. Bertentangan dengan hal ini, seseorang mungkin bersikeras bahwa aturan-aturan yang mengatur imajinasi estetika terpisah dari, karenanya asing bagi, cara kerjanya sendiri. Hal ini karena, seseorang mungkin berpendapat, nilai estetika yang diciptakan oleh aktivitas imajinatif bebas tidak bergantung pada aturan-aturan yang mengarahkan aktivitas tersebut: ekspresi terbesar dari nilai moral atau epistemik dihasilkan dari kesesuaian kita yang ketat dengan hukum-hukum otonom yang mengatur kehendak atau pemahaman bebas kita, sedangkan keindahan asli hanya muncul ketika imajinasi bebas kita tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang mengaturnya.
Namun, jika imajinasi menciptakan atau menghargai sesuatu yang indah, maka aktivitasnya mematuhi norma-norma yang mengatur penciptaan atau penghargaan tersebut. Yang pasti, rasa kepatuhan ini tidak sama dengan kasus moral atau epistemik, tetapi itu hanya karena jenis aturan yang diaturnya berbeda: jika imajinasi estetika beroperasi dengan sukses, ia memenuhi norma-norma yang mengarahkannya dalam satu-satunya pengertian yang tidak pasti yang diperlukan (atau dimungkinkan) oleh aturan yang longgar (berlawanan dengan aturan yang ketat seperti hukum). Misalnya (lih. Bagian X.3), imajinasi berhasil mematuhi arahan akal budi yang samar untuk memperoleh konten representasional yang maksimal jika ia menggabungkan dan memperbesar manifold yang masuk akal dengan cara yang tidak biasa dan menyenangkan secara estetika. Lebih jauh, nilai estetika yang muncul dari aktivitas imajinasi bebas pada dasarnya terikat pada aturan-aturan yang mengatur aktivitas tersebut: karena semua keindahan melibatkan “sensualisasi gagasan moral” (KU, 5:356), dan karena (seperti yang kita lihat) gagasan moral memainkan peran kunci dalam membimbing penciptaan dan apresiasi estetika, nilai moral yang terkandung dalam gagasan-gagasan ini terhubung secara integral (meskipun tidak identik) dengan nilai estetika keindahan. Oleh karena itu, norma-norma intelektual yang mengatur imajinasi bebas tidak asing dengan nilai khas yang ingin diciptakannya melalui cara operasi estetikanya.”
The second reason why the free imagination can be considered autonomous is that it allows rational directives to guide its activity while at the same time refusing to be dominated by them. Free imaginative activity develops the input it receives from intellectual rules in a way that is geared towards its non-moral, non-epistemic, specifically aesthetic telos. It thereby exemplifies the notion of self-determination that is central to Kant’s notion of autonomy. The free imagination determines itself by taking a cue from objective intellectual norms but then interpreting that cue in its own characteristic, subjectively playful manner. The special way in which the aesthetic imagination takes up discursive intellectual content is reflected in the special character of its products: unlike other (moral, epistemic) species of spontaneous activity, the imagination spontaneously determines itself to a symbolic sensible (rather than purely intellectual-conceptual) (re)presentation of the supersensible. This special kind of self-determination allows the imagination to make supersensible rational content amenable to the emotive, sensible side of human nature: to our faculty of feeling.
“Alasan kedua mengapa imajinasi bebas dapat dianggap otonom adalah karena ia membiarkan arahan rasional memandu aktivitasnya, sementara pada saat yang sama menolak untuk didominasi oleh arahan tersebut. Aktivitas imajinatif bebas mengembangkan masukan yang diterimanya dari aturan intelektual dengan cara yang diarahkan pada tujuan estetika yang non-moral, non-epistemik, dan spesifik. Dengan demikian, ia mencontohkan gagasan tentang penentuan nasib sendiri yang menjadi inti dari gagasan Kant tentang otonomi. Imajinasi bebas menentukan dirinya sendiri dengan mengambil isyarat dari norma intelektual objektif, tetapi kemudian menafsirkan isyarat itu dengan caranya sendiri yang khas dan subjektif. Cara khusus imajinasi estetika mengambil konten intelektual diskursif tercermin dalam karakter khusus produknya: tidak seperti spesies aktivitas spontan (moral, epistemik) lainnya, imajinasi secara spontan menentukan dirinya sendiri untuk (re)presentasi simbolis yang masuk akal (daripada murni intelektual-konseptual) dari yang supersensible. Jenis penentuan nasib sendiri yang khusus ini memungkinkan imajinasi untuk membuat konten rasional yang melampaui nalar dapat diterima oleh sisi emosional dan nalar dari sifat manusia: oleh kemampuan kita untuk merasakan.”
If this account (or something akin to it) is on the right track, we can conclude that freedom of imagination qualifies as a genuine species of transcendental freedom: the imagination exemplifies the only type of spontaneous self-determination that fits the aesthetic dimension of human life. My overall interpretation in this book thus establishes the (generic) idea of transcendental freedom as the cardinal point of all three major areas that constitute Kant’s systematic philosophy. Accordingly, Kant can view such freedom as the proper anchor of all meaningful human activity, in moral, epistemic, and aesthetic contexts.
“Jika penjelasan ini (atau sesuatu yang mirip dengannya) berada di jalur yang benar, kita dapat menyimpulkan bahwa kebebasan imajinasi memenuhi syarat sebagai spesies kebebasan transendental yang sejati: imajinasi mencontohkan satu-satunya jenis penentuan nasib sendiri secara spontan yang sesuai dengan dimensi estetika kehidupan manusia. Penafsiran saya secara keseluruhan dalam buku ini dengan demikian menetapkan gagasan (umum) tentang kebebasan transendental sebagai titik kardinal dari ketiga bidang utama yang membentuk filsafat sistematis Kant. Dengan demikian, Kant dapat memandang kebebasan tersebut sebagai jangkar yang tepat dari semua aktivitas manusia yang bermakna, dalam konteks moral, epistemik, dan estetika.”
4. Ringkasan
Mari kitra ringkas pandangan Kohl terhadap Kant.
Kohl meluaskan konteks freedom menjadi tiga: (a) moral; (b) epistemik; (c) estetika. Pandangan umum hanya menerima konteks tunggal bagi freedom: moral.
Makna freedom dalam konteks moral dan epistemik adalah setara: freedom adalah otonomi akal budi untuk (a) menetapkan aturan dan (b) menjalankan aturan. Karena akal yang membuat aturan sendiri kemudian menjalankan aturan itu maka akal adalah bebas.
Ketika akal melanggar aturan maka akal kehilangan kebebasan karena terikat kewajiban untuk menebus pelanggaran tersebut. Jika seseorang ingkar janji maka dia kehilangan kebebasan karena terikat kewajiban untuk menebus kesalahan ingkar janji itu. Tetapi bila seseorang memenuhi janji maka dia tetap bebas apakah berikutnya (a) tetap memenuhi janji atau (b) mengingkari.
Makna freedom dalam konteks estetika adalah unik karena menerapkan kebebasan imajinasi rasa. (a) Imajinasi tidak menetapkan aturan; tetapi imajinasi meminjam aturan intelektual dari moral dan epistemik secara longgar. (b) Imajinasi menjalankan aturan intelektual tetapi tidak sepenuhnya didominasi aturan intelektual tersebut. (c) Imajinasi adalah kebebasan rasa; kebebasan cinta; kebebasan rindu yang unik; karena berbeda dengan kebebasan moral mau pun kebebasan epistemik.
Kontribusi utama dari Kohl, menurut saya, adalah kebebasan epistemik. Akal menetapkan aturan secara bebas; misal aturan kausalitas. Kemudian, akal menerapkan kausalitas itu dengan bebas pada kasus-kasus partikular; misal sinar matahari itu menyebabkan suhu batu bertambah panas. Atau alternatifnya, akal menetapkan aturan korelasi. Kemudian menerapkan bahwa sinar matahari itu sekadar korelasi dengan suhu batu yang bertambah panas.
Kebebasan epistemik di atas menguatkan kebebasan moral. Karena pengetahuan kita adalah bebas maka pilihan sikap moral kita juga bebas. Pada gilirannya, kebebasan moral akan menguatkan kebebasan epistemik. Sikap moral yang baik akan menjamin kemampuan memahami dengan baik.
Bagaimana peran kebebasan rasa estetika?
5. Diskusi
Peran kebebasan rasa estetika adalah paling utama. Kebebasan rasa adalah lembut mempesona.
Kebebasan imajinasi membutuhkan aturan moral. Kita belajar moral dari ibu, keluarga, dan masyarakat luas. Sehingga, kebebasan imajinasi membutuhkan peran penting dari masyarakat luas. Kebebasan imajinasi membutuhkan aturan epistemik (aturan rasional). Aturan epistemik ini membutuhkan sintesa, dalam kadar tertentu, dengan alam raya. Sehingga, kebebasan imajinasi membutuhkan alam raya. Lengkap sudah, untuk meraih bebas imajinasi, bebas estetika, bebas rasa maka kita membutuhkan masyarakat luas dan alam raya.
Bagaimana pun, kebebasan estetika itu tidak didominasi oleh masyarakat mau pun oleh alam raya. Kebebasan estetika selaras dengan masyarakat dan alam raya kemudian menghadirkan keindahan cinta. Mengapa bisa selaras? Selaras adalah anugerah dari sumber anugerah. Kita pantas bersyukur atas semua anugerah.
Bagaimana menurut Anda?